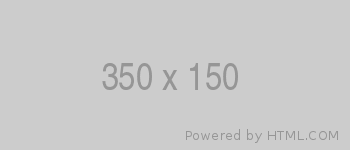“Komunis!”
Seruan itu meluncur bak kutukan yang melekat tiap kali mahasiswa menentang kebijakan yang muncul. Label yang seolah menjadi kutukan abadi, tapi tanpa ada usaha sungguh-sungguh memahami esensi di baliknya. Ironisnya, mereka yang paling keras menuding justru malas membaca buku, karena mereka lebih suka melihat konten standar TikTok yang membuat otaknya menjadi dongo — hingga buta akan dunia literasi. Begitu melihat buku bersampul merah, langsung berujar: “Ah, itu mah komunis! Kamu atheis! Pasti antek antek PKI! PKI! PKI!”
Ironi makin lengkap ketika tudingan itu datang dari mereka yang mengaku pewaris peradaban ilmu dari Baghdad dan Andalusia. Tapi giliran anak muda membaca buku-buku karya tan malaka, bukannya diajak berdiskusi, malah disarankan segera ruqyah. Padahal, Tan Malaka—yang kerap diserang dari segala arah, adalah seorang hafiz Al-Qur’an. Fakta ini sering kali tak dianggap penting. Karena hari ini, yang lebih dihitung bukan isi kepala, tapi seberapa cepat kita melabeli. Kualitas dipinggirkan, kuantitas diglorifikasi. Dan pola pikir seperti itu, sayangnya, masih terus dipelihara dengan bangga sampai sekarang.
Sementara itu, pada Surat Al-Ma’un dalam Al-Qur’an mengecam mereka yang gemar beribadah tapi abai pada nasib anak yatim dan miskin. Ironisnya, ayat-ayat tentang keadilan ini sering diabaikan, sementara siapa pun yang membicarakan nasib tertindas, apalagi dengan diksi yang terdengar “kiri” langsung dianggap sesat. Mungkin karena keadilan, dari mana pun datangnya, memang selalu membuat resah mereka yang nyaman.
Musuh Bersama yang Tak Pernah Duduk Bersama
Islam dan komunisme, dalam wujud aslinya yang paling jujur, sama-sama menempatkan keadilan sebagai ruh utama. Namun keduanya justru berbagi nasib: dicurigai, dibatasi, bahkan dibungkam. Islam kerap direduksi sebagai simbol radikalisme, sementara komunisme tak kunjung lepas dari bayang-bayang masa lalu yang traumatis.
Dalam Pendidikan Kaum Tertindas, Paulo Freire menegaskan bahwa pembebasan tak bisa hanya dilakukan oleh pihak yang tertindas, ia harus mengajak yang menindas untuk berubah. Sementara Tan Malaka, melalui Madilog, menyerukan penggunaan akal sehat dan logika sebagai senjata melawan feodalisme. Dan The Communist Manifesto, pamflet klasik Marx dan Engels, hanya ingin satu hal: melepaskan pekerja dari jeratan ketidakadilan struktural.
Tapi di negeri ini, suara-suara itu tak pernah benar-benar mendapat tempat. Gagasan yang menyala terlalu terang dianggap menyalahi aturan. Keadilan dibaca sebagai isyarat subversif. Dan mereka yang mengusungnya, entah lewat ayat atau selebaran kiri, dianggap menyimpang dari jalan yang sah.
Ketakutan yang Sistemik
Menurut survei Yayasan Penelitian Indonesia (2023), 60 persen mahasiswa Indonesia menyatakan enggan membicarakan komunisme, bukan karena paham, tapi karena takut. Takut dituduh, dicap, bahkan dipantau. Bahkan 42 persen lainnya mengaku belum pernah membaca karya kiri, namun sudah yakin bahwa komunisme adalah ancaman moral dan ideologis.
Di banyak forum, keberanian berpikir diganti dengan keberanian melabeli. Kritik dijawab dengan ad hominem, argumen dibalas dengan tudingan, dan siapa pun yang berbeda langsung dicap “terpapar.” Kita tidak sedang krisis iman—kita sedang krisis otak. Lebih tepatnya: otak dongo yang malas membaca tapi rajin menuduh.
Di Antara Kritik dan Ketegangan
Tentu, tak semua kalangan menerima gagasan bahwa Islam dan komunisme punya titik temu. Kritik datang dari kubu Islam konservatif yang menolak mentah-mentah segala bentuk simpati terhadap Marxisme. Mereka mengingat sejarah kelam 1965, tragedi berdarah yang menorehkan luka di tubuh bangsa. Bagi mereka, komunisme dan Islam tidak mungkin berdampingan: satu ateistik, satu teistik.
Penolakan ini valid. Tapi kekeliruan muncul ketika penolakan itu melahirkan ketertutupan. Menolak membaca karena takut “terpapar” adalah bentuk kepanikan yang tidak ilmiah. Seperti menolak belajar kedokteran karena takut jadi kafir.
Penutup: Yang Sebenarnya Ditakuti
Kita tidak sedang membela komunisme, apalagi hendak menistakan Islam. Yang sedang coba kita lakukan hanyalah menyampaikan sesuatu yang barangkali sederhana: bahwa keadilan, tak peduli datang dari kitab suci atau dari lembaran Manifesto Komunis, akan selalu terasa mengancam bagi mereka yang menggantungkan hidup dari ketimpangan.
Membaca buku tak pernah membuat seseorang murtad. Yang membuat kita kehilangan arah justru ketika membaca dianggap dosa, dialog dituduh sesat, dan berpikir diganti dengan slogan. Di situlah kebodohan menjadi sistemik—dibiarkan, bahkan dipelihara.
Dan kebodohan yang dilembagakan adalah bentuk penindasan yang paling rapi: tak kelihatan, tapi bekerja setiap hari.
Maka barangkali, yang selama ini ditakuti bukanlah komunisme, bukan pula Islam yang bicara terlalu keras.
Yang benar-benar menakutkan adalah: keadilan itu sendiri.
Karena keadilan yang dijalankan secara konsisten, cepat atau lambat, akan mengguncang kenyamanan mereka yang selama ini duduk terlalu manis di puncak piramida.