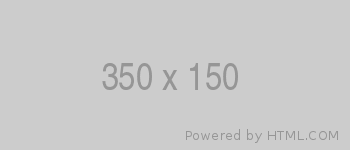Kritik atas matinya intelektualitas dan lahirnya mentalitas simbolik di kalangan calon sarjana hukum Universitas Islam Malang
Secara berurutan, dalam konteks sosiokultural mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, elitis dapat dimaknai sebagai budaya yang mengagungkan status, koneksi, serta simbol prestise ketimbang substansi akademik. Eksklusif mencerminkan sikap tertutup terhadap pandangan baru, wacana kolaboratif, apalagi kritik. Sedangkan degeneratif tampak nyata di depan mata kita ketika dewasa ini institusi FH Unisma mengalami kemunduran kualitas moral dan intelektual—sebuah kondisi yang menandai penurunan daya hidup akademik secara sistemik.
Elitis dan eksklusif telah menjelma menjadi watak sebagian besar calon sarjana hukum. Hal ini tercermin dari budaya kehidupan kampus yang selama ini penulis amati dan jalani. Umumnya, mahasiswa Fakultas Hukum adalah mereka yang tampil rapi dan necis, baik di dalam maupun di luar kampus. Budaya ini di satu sisi memang merupakan refleksi dari dunia kerja hukum yang identik dengan kerapian dan keteraturan advokat, jaksa, hakim, notaris, dan sebagainya. Namun, di sisi lain, budaya ini juga tumbuh dari mentalitas gengsi dan biaya pendidikan yang tinggi, di mana simbol-simbol prestise lebih diagungkan daripada isi kepala.
Di era digital ini, selain kerapian dan kenecisan, kemolekan kendaraan, kecantikan hasil foto gawai, dan keestetikan unggahan Instagram seolah menjadi tolok ukur baru derajat mahasiswa hukum. Pertanyaannya: apakah kerapian berpakaian mencerminkan kerapian berpikir mereka? Apakah keteraturan jas dan kemeja itu juga menandai keteraturan nalar dalam memahami dinamika hukum Indonesia? Apakah estetika yang mereka agungkan di dunia maya akan berguna untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum di negeri ini?
Dalam bukunya Finding the Law: A Guide to Legal Research, David Lloyd menegaskan bahwa sebelum menjadi seorang legal researcher, calon sarjana hukum semestinya terlebih dahulu menyusuri belantara perpustakaan hukum, menelaah karya para pendahulu, dan mengapresiasi produk hukum yang lahir dari sejarah panjang perjuangan intelektual. Bentuk apresiasi itu bukan berupa sanjungan dan tepuk tangan, melainkan usaha nyata memahami dan mengkritisi karya serta produk hukum tersebut secara ilmiah. Namun, bagaimana mungkin hal itu bisa dilakukan bila sebagian mahasiswa bahkan telah menyerah pada kebosanan kelas dan bacaan? Bagaimana mungkin intelektualitas tumbuh bila yang tersisa hanyalah keacuhan kolektif terhadap keadaan?
Tan Malaka pernah berkata, “Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali.”
Pernyataan cadas dari Bapak Republik ini terasa relevan untuk memotret keadaan calon sarjana hukum Unisma hari ini. Masalahnya, banyak dari mereka lebih dulu merasa pintar daripada benar-benar belajar—sebuah kondisi yang bahkan lebih parah daripada yang dikhawatirkan Tan Malaka.
Dari sekian ratus mahasiswa aktif Fakultas Hukum Unisma, seberapa banyak yang sungguh membaca buku-buku hukum di perpustakaan kampus? Atau setidaknya menjadikannya referensi dalam menyusun tugas? Penulis tidak tahu pasti. Namun, penulis berani bertaruh, angka itu mungkin tidak sampai tiga puluh persen. Dua puluh persen saja sudah termasuk kemewahan intelektual bagi Fakultas Hukum hari ini.
Dengan kemudahan akses internet, apalagi dengan hadirnya kecerdasan buatan, banyak calon sarjana hukum merasa diri mereka sudah cukup dalam hal belajar dan mengerjakan tugas. Cukup mengetik beberapa kata, maka semua jawaban seolah tersedia dan dapat mereka percaya. Ironisnya, kemudahan itu tidak mendorong mereka untuk tekun belajar, berdiskusi, dan bernalar, melainkan justru membuat mereka semakin terbuai dan tersesat dalam kenyamanan semu digital.
Fenomena ini mudah terlihat dalam kelompok-kelompok tugas. Presentasi dibuat, tetapi tak satu pun memahami materi. Microsoft PowerPoint menjadi alat dongeng akademik—slide demi slide dibacakan tanpa pemahaman dan penguasaan. Ketika sesi tanya jawab dibuka, tangan-tangan mereka sigap menggenggam ponsel, bukan untuk mencatat, melainkan untuk mengetik pertanyaan ke AI. Jawaban yang muncul kemudian mereka bacakan kembali tanpa pemahaman, seolah kecerdasan buatan bisa menggantikan proses belajar mereka di ranah legal.
Lebih jauh lagi, muncul pula kalangan mahasiswa yang menjadikan uang sebagai sarana utama kelulusan. Dengan beberapa digit rupiah, mereka menyewa joki tugas dan membeli nilai. Tidak ada yang lebih penting bagi mereka selain menyelesaikan kelas, UTS, dan UAS, meski nilai dan isi kepalanya berbanding terbalik dengan gelar yang kelak disandang.
Degeneratif di lingkungan Fakultas Hukum Unisma adalah fakta, dan kita semua menyadarinya. Namun, apa yang akan kita perbuat selanjutnya? Akankah terus bergantung pada kemajuan zaman dan memilih untuk tetap begini-begini saja? Ataukah kita akan mewujudkan kesadaran itu menjadi gerakan nyata?
Kita tidak bisa membiarkan Fakultas Hukum Unisma menuju kematiannya sendiri. Nyawa dan marwahnya harus terus kita rawat dan jaga. Fakultas Hukum Unisma harus tetap menjadi kawah candradimuka pembentukan nalar kritis dan integritas, bukan panggung formalitas intelektual. Hukum tidak boleh menjadi sekadar kostum kehormatan, melainkan disiplin berpikir. Fakultas Hukum Unisma harus melahirkan sarjana yang tahu bagaimana caranya bermakna, bukan sekadar pengguna toga yang kebingungan akan identitasnya.
Matinya hukum bukan ketika keadilan hilang, melainkan ketika para sarjananya berhenti bertindak bijak dan berpikir tajam.
Salam Masyarakat Baru!