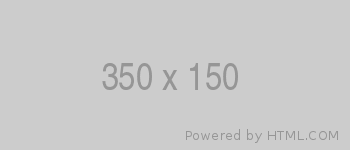Dalam berorganisasi, baik di kampus, lembaga kemasyarakatan, atau institusi pemerintahan, kritik kerap dipersepsikan sebagai gangguan. Terlebih ketika kritik itu datang dari orang-orang yang ada pada kelompok itu. Alih-alih diperlakukan sebagai masukan, kritik sering dianggap pembangkangan, bahkan ancaman terhadap kewibawaan seorang ketua.
Ketua yang menutup diri dari kritik sejatinya sedang membatasi kemampuan organisasinya untuk belajar. Kepemimpinan tidak hanya soal mengarahkan dan memutuskan, tetapi juga tentang kemampuan mendengar. Kritik dalam berorganisasi, bukan serangan personal, melainkan mekanisme koreksi yang lahir dari realitas kerja sehari-hari yang sering luput dari penglihatan pemimpin di puncak struktur.
Dalam kajian kepemimpinan modern, Peter Drucker menilai kemampuan menerima kritik dipandang sebagai indikator kedewasaan pemimpin. Pemimpin yang defensif, yang selalu merasa perlu membela diri saat dikritik, cenderung memusatkan energi pada perlindungan citra pribadi, bukan pada perbaikan sistem. Kritik lalu dipelintir menjadi persoalan loyalitas, bukan kualitas keputusan. Akibatnya, ruang dialog menyempit dan organisasi kehilangan kecerdasan kolektifnya.
Penolakan terhadap kritik juga melahirkan budaya yang berbahaya. Dalam situasi seperti ini, informasi yang mengalir ke atas bukan lagi gambaran objektif keadaan, melainkan versi yang telah disaring agar tidak menyinggung atasan. Masalah disembunyikan, risiko dikecilkan, dan kegagalan ditunda pengakuannya. Padahal, organisasi hanya bisa berkembang jika berani berhadapan dengan fakta, sekeras apa pun itu.
Menerima kritik bukan berarti mengiyakan semua masukan. Kritik tetap perlu diuji, diverifikasi, dan dipertimbangkan secara proporsional. Namun, proses mendengarkan itu sendiri adalah bentuk penghormatan terhadap kerja kolektif. Ia menegaskan bahwa organisasi bukan milik satu orang, melainkan milik bersama.