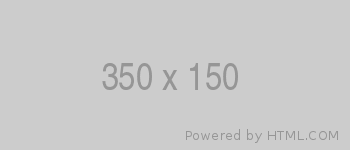Cahaya hangat mentari mulai menembus celah-celah jendala. Ruangan 9×8 m penuh dengan hiruk pikuk suara canda tawa. Kursi dan meja yang berbaris rapi perlahan mulai terisi. Ruangan itu tampak mulai ramai diduduki oleh bokong-bokong. Suasana hangat yang menyeruak menggantikan dingin yang menyergap.
Tetapi, lihatlah seseorang yang tengah duduk di barisan belakang tepi jendela itu. Anak laki-laki dengan tinggi 180 cm terus menatap keluar jendela. Tatapan sendunya terus terpaku pada sebuah lapangan basket yang tak jauh dari kelasnya. Sesekali bibinya mengukir senyum getir seakan menusuk kedalam hati.
Tringgg…
“Ayo masuk pak guru datang,” ucap Dika sambil melambai-lambaikan tangan.
“Eh, katanya ada siswi pindahan dari jepang ya hari ini?” Bisik beberapa siswa yang sedang bergibah.
“Aku juga mendengarnya begitu, katanya dia orang Indonesia tapi sudah lama menetap di Jepang dan sekarang dia kembali karena pekerjaan ayahnya,” sambung salah satu siswi.
“Tidak, tidak mungkin dia.” Jino membatin. Tapi, selanjutnya ia kembali menatap keluar jendela.
Beberapa menit setelahnya, Pak guru datang, di belakangya seorang siswi cantik mengikuti. Wanita dengan kulit putih dan rambut setengah dikuncir. Ia tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek, yang artinya sedang.
Setibanya siswi itu ke dalam kelas, mata mungilnya spontan tertuju pada sosok yang tak asing baginya. Seseorang yang telah ia kenal, seseorang yang telah lama membuatnya rindu.
“Baik, Anak-anak. Duduk yang rapi,” tatih pak guru.
“Wahh cantik bro.” Riko berseru sambil menepuk bahu Dika.
“Heh, Kalian. Jangan berisik, terutama kamu, Riko” Tegur Pak guru.
“Anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru yang akan bergabung dengan kelas ini, dia pindahan sekolah dari jepang. Silakan, bisa perkenalkan diri kamu!” Pak guru mempersilakan.
“Hai, Teman-teman. Perkenalkan namaku Selia, aku pindahan dari jepang, senang bisa bergabung di kelas ini, semoga kita bisa berteman baik,” ucap Selia sambil tersenyum, tatapannya masih jatuh pada seseorang yang telah mencuri perhatiannya sejak masuk tadi.
Saat mendengar nama itu disebut, tubuh Jino terasa kaku, seakan waktu memilih berhenti sejenak. Suara itu menggema di kepalanya, melingkupi seluruh saraf dalam tubuhnya. Perlahan, tanpa sadar, matanya bergerak mengarah ke depan, meski hati kecilnya berteriak untuk tetap berpaling. Ada rasa cemas yang tiba-tiba menggulung. Tatapannya menangkap sosok yang begitu ia kenal, seseorang yang selama ini tak berharap ia temui lagi. Selia berdiri di sana, seperti bayangan yang muncul di tengah kabut pagi.
“Kenapa harus sekarang, kenapa harus saat keadaan seperti ini,” bisik Jino dalam hati, lalu memalingkan pandangannya kembali.
“Selia, sila duduk di kursi kosong belakang,” Pak Guru tersenyum sembari menunjuk sebuah kursi kosong di bagian belakang.
“Baik, Pak. Terima kasih,” ucap Selia membalas senyumnya.
Selia melangkah menuju tempat duduknya. Beberapa pasang mata memandang ke arahnya. Terlebih para siswa laki-laki, bola mata mereka seperti menangkap magnet pada tubuh Selia. Namun, tidak dengan seseorang dibangku dekat jendela paling belakang. Seseorang yang tak asing itu. Jino terus memalingkan muka dan pandangannya.
“Hai, senang bertemu kamu lagi,” sapa Selia berusaha terlihat biasa saja.
“Aku harap kamu baik-baik saja,” batin Selia. Ia tersenyum, entah apa yang mendorongnya melakukan itu.
Setelah sekian lama, suara itu terdengar lagi membuat hati Jino mulai merasakan kehangatan. Kehangatan yang selama bertahun-tahun hilang. Meski ia ingin sekali membalas dan memandang Selia, otaknya terus menolak. Rasa malu dan takut yang dirasakan Jino selalu menghatui layak kabut yang tak pernah putus.
***
Bel tanda pulang sekolah yang bunyinya lantang telah mengema ke seluruh penjuru sekolah. Para siswa berbondong-bondong keluar kelas, segera pulang untuk melepas penat mereka. Setelah kelas mulai sepi karena ditinggalkan oleh para penghuninya, Jino segera keluar kelas. Ia berjalan pelan dan hati-hati karena masih belum terbiasa berjalan menggunakan tongkat. Meski sudah cukup lama menggunakan gagang kayu tersebut, ia belum bisa beradabtasi dengan baik.
Langkahnya mulai terhenti ketika sampai ditengah lapangan basket. Rasa sesak langsung merayap ke seluruh tubuhnya. Matanya memandangi sekitar seakan-akan mengulangi memori masa lalu. Jino melihat jam di tangan kanannya, ternyata masih ada waktu sebelum supir jemputannya datang. Jino memutuskan untuk duduk di samping lapangan menikmati suasana sekolah yang sudah sepi.
Ia mencoba memejamkan mata, memori indah itu langsung berputar bagai klip film di kepala. Memori saat dengan semangatnya ia berlatih di lapangan ini, memori saat ia bisa mencetak skor terbanyak, memori saat bermain basket bersama teman-teman klub basketnya, serta kenangan-kenangan lainnya yang masih banyak lagi.
Saat pikirannya sedang asik mengingat kenangan-kenangan itu, tiba-tiba terdengar seperti suara langkah kaki yang semakin dekat. Saat ia membuka matanya dan menoleh kesamping, Selia sudah duduk di sebelahnya, menyambutnya dengan senyuman khasnya, senyuman yang terlihat masih sama.
“Astaga, kau mengejutkanku,” Jino terperanjat.
“Hai, Jino.” Selia menyapa.
“Kok kamu masih disini? Sekolah kan udah sepi,” tanya Jino kembali mengarahkan wajahnya ke depan.
“Hm… aku habis dari toilet gak segaja melihatmu sendirian,” jelas Selia tersenyum.
“Ternyata kamu masih ingat aku,” ucap Jino, membalas senyumnya.
“Aku gak bakal lupain kamu apapun keadaannya, tapi kenapa kamu tadi seperti menghindar?” Tanya Selia. Kini terlihat sangat berharap jawaban dari Jino.
“Eh…Aku hanya malu untuk ketemu kamu di saat keadaanku seperti ini, kamu bisa lihat sendiri” jelas Jino dengan kepala tertunduk.
“Bahkan, sekarang aku gak berharap bertemu kamu lagi Sel, aku udah gak seperti dulu lagi,” lanjutnya.
Mata Jino tertuju pada salah satu kakinya yang telah teramputasi, spontan mata Selia ikut melirik kakinya.
“Apapun keadaan kamu, kamu tetap Jino yang dulu tidak akan berubah sedikit pun, Jino seorang atlet basket yang sangat keren, sekaligus sahabat kecil yang menyebalkan,” ujar Selia tertawa.
Sebenarnya Jino juga ingin ikut tertawa, tapi entah kenapa hanya senyuman yang mampu ia ukir di wajahnya yang penuh sedih.
“Kalau boleh tau, apa yang sebenarbya terjadi pada mu, Jino?” Tanya Selia.
Jino tak langsung menjawab. Sejenak ia menarik napas panjang. Tampak sekali betapa sulitnya ia mengingat kejadian itu. Kejadian yang ia anggap akhir dari semangatnya menjalani hidup ini.
“Aku mengalami kecelakaan saat berangkat latihan persiapan turnamen, dan ya akhirnya seperti yang kamu lihat, tapi tenang saja aku tidak apa-apa, jangan menatapku dengan tatapan kasihan, aku tak menyukai itu,” pintanya tersennyum getir.
“Sebenarnya Papa sudah membelikan aku kaki robot agar aku bisa bermain basket lagi, tapi aku tak yakin bisa seperti dulu,” ujar Jino mengusap rambutnya yang sebenarnya tak berantakan.
“Tidak apa apa jika kamu tidak siap, tetapi menurutku kamu tidak boleh menyerah sama impianmu, aku tau ini impianmu sejak , Jino. Setidaknya kamu harus mencobanya, aku yakin kamu pasti bisa meraih medali emas bahkan lebih.” Selia mencoba menyemangati pria di hadapannya.
“Kamu tau gak apa yang aku sukai darimu sejak kita kecil?” Tanyanya kemudian.
“Apa?” Jino tampak sedang menunggu.
“Aku suka saat kamu bermain basket, aku harap kali ini aku bisa melihatmu bermain basket lagi secara langsung, seperti dulu, sekeren Jino yang dulu,” ujar Selia menatap Jino lekat.
Senyuman.
“Hah.. maksudnya?” timpal Jino tak mengerti.
“Iya, kan ini udah akhir kelas, saatnya kita pulang. Ya Sudah aku udah dijemput, aku pulang dulu ya, da… Jino”
Selia melambaikan tangan, tak pernah ketinggalan senyumnya yang manis, dengan lincah kakinya melangkah meninggalkan lapangan, perlahan tubuh rampingnya tak lagi tampak dari pandangan Jino.
Setelah mobil Jemputan Jino datang ia segera pulang ke rumah. Mobil itu melaju menembus ramainya jalanan sore dengan langit jingga yang begitu indah. Setibanya ia di rumah, Ia langsung menuju kamarnya, menghempaskan badannya yang lelah di kasur empuknya.
Tak terasa, hari mulai gelap. Ia tak mengintip jendela atau melirik jam dinding, suara panggilan ibu mengajak Jino makan sudah memberi tanda bahwa makan malam sudah tiba.
“Wah enak banget bu makanannya,” puji Jino dengan mulut yang masih sesak dengan makanan.
“Kamu suka, kalau suka besok akan Ibu masakin lagi?” Mama tersenyum.
“Gitu dong makan yang lahap biar kenyang” Ayahnya menimbrung.
“Oh ya, Yah. Setelah Jino pikir-pikir, Jino mau pakai kaki robot itu, Jino juga mau bermain basket lagi,” ujar Jino dengan penuh keyakinan, makanan di piringnya baru saja termakan beberapa sendok.
“Syukurlah, gitu dong baru anak Ayah. Ayah yakin kamu pasti bisa,” tegas Ayah.
“Iya, Nak. Ibu juga yakin kamu juga akan menjadi atlet yang terkenal suatu saat nanti apapun keadaan kamu” Ucap Ibu tersenyum.
***
Setelah melakukan latihan rutin, tentu karena kesabaran Ayah membatunya dalam proses ini. Kini, ia datang ke sekolah tidak lagi bersandar pada tongkat yang akhir-akhir ini setia menemaninya. Jalannya perlahan kembali tegap, kaki robotnya bergerak seirama dengan langkahnya, walaupun masih belum semantap dulu.
Seperti gelombang yang pecah di karang, kehadirannya menyapu perhatian seluruh siswa di lorong sekolah. Tatapan mereka tertuju padanya, penuh rasa takjub. Jino yang dulu mereka kenal penuh semangat dan keyakinan telah kembali. Ia bagaikan matahari yang terbit setelah malam panjang, membawa sinar baru yang berhasil mencuri tatapan mata.
Saat bel istirahat berdentang, lapangan basket menjadi sasaran utamanya, tempat yang selalu menjadi panggung mimpinya. Di sana, ia mendapat sambutan hangat dari teman-temannya. Kehadiran Jino bagai menemukan kepingan puzzle yang hilang, melengkapi tim mereka yang selama ini terasa tak utuh tanpa sang kapten. Dengan senyum tipis, Jino memutuskan bergabung dalam permainan, mencoba menyesuaikan diri kembali dengan irama yang pernah begitu akrab. Walaupun ia masih menyadari, gerakannya tak bisa selincah seperti dulu. Yah, setidaknya ia tak menjadi orang pasrah seperti kemarin, ada semangat untuk mencoba pun sudah menjadi hal yang paling berani yang selama ini ia lakukan.
Di sudut lapangan, Selia berdiri. Tatapannya lembut, penuh harap, menyaksikan setiap gerak Jino. Ketika Jino berhasil memasukkan bola ke dalam ring dengan gemilang, senyum manis mengembang di wajah Selia, seolah matahari pagi baru saja terbit di hatinya. Ia bersorak pelan, kagum, menatap Jino yang telah kembali dengan semangatnya yang tak pernah padam, seakan angin kemenangan mulai berhembus lagi.
Ia memang kembali ke dalam tim itu, tapi ia paham dengan keadaanya, ia tak mungkin kembali pada posisinya sebagai kapten. Ia masih membutuhkan latihan yang lebih rutin lagi akar kaki robot pemberian Ayahnya itu betul-betul telah menjadi bagian dari tubuhnya.
Setiap pulang sekolah, Jino tak pernah absen berlatih. Lapangan basket kini menjadi rumah keduanya. Mimpi besar tumbuh kembali, melampaui batas tubuhnya yang baru.
Setiap selesai jam pelajaran, Selia sering hadir di sisi Jino, seperti bayangan yang tak pernah jauh. Mereka menghabiskan waktu bersama, seolah menghidupkan kembali kenangan masa kecil mereka yang penuh keceriaan. Tawa dan canda mereka bergema di udara sore, menciptakan lukisan indah tentang persahabatan dan harapan yang tak pernah pudar. Bagaikan dua jiwa yang saling melengkapi, kehadiran Selia menjadi penyemangat, sementara Jino adalah wujud dari mimpi yang tak pernah menyerah.
“Nih minum dulu,” Selia memberikan sebotol air kepada Jino.
“Terimakasi, Sel.” Jino dengan nafas teregah-engah dan tubuh basah dengan keringat meraih sebotol air minum dari gadis yang dicintainya.
“Kamu hebat sekali, ini baru Jino yang aku kenal. Aku bangga banget sama kamu.” ujar Selia, tak pernah melewatkan senyum termanisnya.
Hari itu, tepat hari Jumat, berakhir dalam hangatnya tawa mereka, melayang bersama angin senja di bawah langit yang menjingga. Seolah matahari yang terbenam turut menyaksikan kebahagiaan kecil yang terukir di antara mereka, membiarkan cahaya terakhirnya memeluk siluet Jino dan Selia. Langit seakan melukis cerita mereka, sementara senyum dan canda memenuhi udara sore yang mulai meredup. Seperti dua bintang yang saling menemukan di ujung senja, hari itu ditutup dengan keindahan sederhana yang tak terucapkan, tetapi berhasil membekas di hati, abadi, selamanya.
***
Enam bulan telah berlalu. Hari dimana pertandingan turnamen nasional itu tinggal satu hari lagi. Ya, tepatnya besok. Jino dengan giat dan penuh semangat berlatih selama berbulan-bulan. Kemampuannya juga meningkat sangat pesat. Tak heran dia ditakdirkan terlahir sebagai atlet.
Jino terus menggenggam bola basket, memantulkannya di lapangan seperti denyut nadi yang tak pernah berhenti. Setiap pantulan menggema di telinganya, pikirannya terbang jauh. Selia, seperti bintang yang meredup di langit malam, tak lagi terlihat selama seminggu ini. Setiap kali Jino mengirimkan pesan, rasanya seperti melempar bola ke dinding tanpa harapan akan pantulan balik. Janji Selia untuk hadir di turnamen esok terasa semakin kabur.
Benar yang dikhawatirkan Jino. Setiba di tempat pertandingan, lapangan yang berkilauan seperti panggung besar yang menanti para bintang bersinar, sorak-sorai penonton menggema, melayangkan semangat seperti ombak yang menghantam pantai, sementara matahari bersinar terang di atas kepala mereka. Di antara ribuan mata yang menatap, ada sepasang mata yang paling berarti bagi Jino, tatapan tulus penuh bangga kedua orang tuanya menjadi bagian dari kekuatannya. Namun, ada lagi sepasang mata yang sangat ia harapkan kehadirannya, ia memperhatikan semua wajah penonton, tak ada Selia di sana. Lalu, kemana gadis itu, kemana janjinya untuk menemaninya di hari perjuangan ini?.
Pertandingan dimulai, Jino dan timnya terlihat kompak dengan gerakan lincah. Bola basket memantul bagai irama musik, dan setiap tembakan melesat seperti anak panah yang tepat sasaran. Skor terus bertambah, membuat lawan tersudut, tak berdaya menghadapi serangan bertubi-tubi. Hingga akhirnya, peluit panjang berbunyi, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak. Medali emas kini tergantung di leher mereka, berkilauan seperti mimpi yang akhirnya menjadi nyata.
Namun, di tengah kebahagiaan itu, mata Jino terus mencari, berharap menemukan sosok yang telah ia nanti. Pandangannya menyapu setiap sudut penonton, namun Selia tak ada di sana. Sosoknya tak hadir, hatinya kini tenggelam dalam kekecewaan. Jino berusaha tetap tersenyum, karena mimpinya telah terwujud ia berdiri di puncak, seorang pemenang meski dengan keterbatasan yang ia miliki.
Setelah pertandingan selesai, Jino segera meminta izin kepada orang tuanya dan teman-temannya. Dengan hati penuh khawatir ia berlalu pergi. Jalanan sore yang ditembusnya terasa panjang, seolah waktu enggan bergerak maju. Medali emas yang masih menggantung di lehernya berkilauan dalam cahaya matahari yang perlahan tenggelam, bersamaan dengan bayangan Selia selalu terlintas di pikirannya. Sahabat yang menjadi cahaya dalam langkah-langkah perjuangannya.
Jino tiba di depan rumah Selia, langkahnya terhenti mendadak, mematung. Pandangannya tertuju pada bendera kuning yang berkibar dengan angin sore yang dingin, seolah waktu berhenti dan seluruh dunianya ambruk dalam sekejap. Kakinya terasa berat, seakan menolak untuk melangkah lebih jauh. Bingung dan tak percaya, Jino melangkah gontai menuju pintu. Berharap kehawatirannya tentang Selia adalah kesalahan semata.
Ayah Selia menggiringnya masuk dengan wajah duka yang dalam. Di dalam, suara orang-orang terdengar sayup, namun hati Jino tenggelam dalam keheningan yang menghantamnya seperti ombak besar yang menghancurkan karang. Ia belum tahu sosok di balik kain putih itu, tetapi foto yang terpajang di hulunya telah menjawab bahwa tubuh yang telah tertutup kain putih adalah wanita yang beberapa hari ini mengganggu pikirannya.
Ayah dan Ibu selia menyampaikan berita duka ini dengan sesak. “Selia tak mau kamu tahu tentang sakitnya.” Kata-kata itu menggema di benaknya, menghancurkan setiap harapan yang telah ia bangun. Medali emas yang semula terasa berat dengan kebanggaan, kini serasa tak ada artinya. Hati Jino retak, hancur berkeping-keping seperti kaca yang dilempar ke lantai. Sahabat yang menjadi alasannya untuk terus bangkit, untuk mencapai titik ini, kini telah meninggalkannya saat akhirnya ia berhasil. Kemenangan yang dirasakannya berubah menjadi kehampaan, dan yang tersisa hanyalah luka di hati yang rasa-rasanya tak mudah ia sembuhkan.
Editor : Safira Ramadani mahfud